Julyan.com | Puluhan ribu batang bibit hutan bakau (manggrove) yang ditanam di sejumlah kawasan pesisir Aceh, belum berjalan sebagaimana harapan. Kebanyakan manggrove tersebut mati. Padahal sudah beberapa kali dilakukan penggantian bibit. Seperti yang terlihat di kawasan pesisir Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Walaupun penggantian bibit sudah dilakukan berkali-kali, namun tetap saja manggrove tersebut tidak bisa hidup dengan baik.
“Di sini sudah beberapa kali dilakukan penanaman bakau, tapi banyak yang mati. Bibit yang sudah sekian lama ditanam, juga belum besar, masih seperti waktu pertama kali ditanam. Harapan untuk hidup tipis,” ungkap Sulaiman, salah seorang petani tambak di desa Lambada, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.
Di kawasan ini, sepanjang jalan Malahayati, arah Krueng Raya, Aceh Besar, terlihat hamparan tambak yang dipenuhi manggarove. Namun, kondisinya sangat memperihatinkan. Batangnya kecil, seukuran jari tangan, dengan ketinggian selutut orang dewasa. Daunnya masih bisa dihitung jari. Bahkan sebagian lain terendam air. Ada juga yang hanya tinggal batang kering.
“Jangankan untuk menahan gelombang besar, dengan air pasang saja mangrove-mangrove tersebut sudah bisa ditenggelamkan,” ujar Sulaiman.
Berdasarkan pengalamannya, pada penanama tahap pertama dan kedua hanya ratusan bibit yang berhasil hidup. Sedangkan puluhan ribu batang lainnya mati. Ia menilai, gagalnya penanaman tersebut disebabkan hampir seluruh bibit bakau terendam air pasang. Daunnya tenggelam. Akibatnya batang-batang muda itu membusuk. Lalu mati.
Penanaman bibit manggrove pada tahap pertama dan kedua untuk penghijauan pantai pasca tsunami di beberapa lokasi di daerah ini mencapai 25.000 batang, sedangkan tahap ke tiga ditanam sekitar 12.000 batang. Diperkirakan, ratusan ribu batang bibit manggrove mati setelah beberapa kali dilakukan pergantian dengan bibit yang baru. Program penghijauan hutan pantai sebagai “benteng” abrasi dan gelombang laut di Provinsi Aceh belum berjalan sebagaimana diharapkan.
Hal itu disebabkan kerena, program hutan pantai yang ditangani Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh- Nias (BRR) dengan melibatkan beberapa kalangan NGO/LSM, tanpa adanya perawatan setelah penanaman. Padahal, untuk merehabilitasi hutan manggrove di Aceh, telah dicanangkan program Green Coast. Program ini, ditargetkan bisa menanam sebanyak 1,2 juta bibit mangrove.
Program yang dilaksanakan atas kerja sama dengan Wetland Internasional Indonesia dengan Word Wild Fund (WWF) tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, mampu merehabilitasi seluas 600 hektare hutan manggrove di Aceh. Pada tahap kedua, rehabilitasi yang dilakukan mencapai 2.700 hektare lahan pertambakan di seluruh Aceh.
Melalui rehabilitasi tambak, diharapkan bisa menghasilkan potensi pengembangan ekonomi. Seperti, pengembangan ekowisata, pengembangan tambak berkelanjutan yang dipadukan dalam kawasan manggrove, kerajinan tangan dan produk makanan. Hal ini merupakan bentuk perpaduan upaya rehabilitasi kawasan hutan manggrove dengan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai pengelola kawasan.
Selain itu, untuk mengelola hutan di pinggiran sungai dan pantai di Aceh, pemerintah telah mendirikan Mangrove Center sebagai lembaga khusus untuk pengelolaan mangrove di Aceh. Namun sayangnya, gedung yang menghabiskan anggaran ratusan juta bantuan pemerintah asing tersebut, sampai saat ini belum berfungsi.
Gedung yang terletak di jalan Cut Nyak Dhien berdampingan dengan Badan Pengelolaan Das Krueng Aceh (BPDKA) itu, tampak begitu sepi. Pintunya tergunci rapat, petanda tidak ada kehidupan di sana. Yang ada, kendaraan pegawai BPDKA terparkir rapi di depan gedung.
“Gedung ini digunakan untuk pertemuan saja. Itu pun jarang-jarang. Karena untuk kegiatan rutinnya itu, di Medan. Di sana regionalnya untuk wilayah Sumatera Utara. Aceh juga merujuk ke sana. Kalau gedung ini memang tidak ada orang. Jangankan untuk aktifitas, untuk lainnya juga belum bisa dimanfaatkan, karena belum ada listrik,” ungkap Effendi salah seorang pegawai BPDKA.
Selain di Banda Aceh dan Aceh Besar, hutan bakau tersebar di kabupaten Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Selatan dan Pidie serta beberapa pulau kecil. Total luas hutan ini sebesar 54.335 hektare.
Hutan bakau umumnya tumbuh di muara sungai dan daerah pasang surut atau tepi laut. Tumbuhan ini unik, karena ia merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut.
Bakau mempunyai sistem perakaran menonjol yang disebut akar napas. Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen. Ada beberapa jenis yang terkenal, di antaranya apa yang biasa disebut bakau itu sendiri atau rhizopora, api-api (avicennia), pedada (sonneratia) dan tanjang (bruguiera). Hutan ini menjadi pelindung alami untuk menahan abrasi pantai. Selain itu, bakau dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar, bahan alkohol, gula, bahan penyamak kulit, bahan atap dan bahan perahu.
Jika hutan bakau hilang, tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, namun manusia dan hewan juga ikut merasakan akibatnya. Seperti, abrasi pantai, membuat intrusi air laut lebih jauh ke daratan, banjir, perikanan laut menurun, dan pendapatan penduduk setempat praktis akan berkurang.
Hutan bakau tersebar di kabupaten Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Selatan dan Pidie serta beberapa pulau kecil. Total luas hutan ini sebesar 54.335 hektare.
Sebelum bencana tsunami, hutan bakau di Aceh telah mengalami kerusakan seluas 2.442,69 hektare di kawasan hutan dan 344.401.08 di luar kawasan hutan bakau. Setelah bencana, kerusakan makin bertambah. Berdasar data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada 2005 kerusakan akibat tsunami seluas 25.000 hektare. Dan menurut Dinas Kehutanan, luas areal yang potensial untuk direhabilitasi seluas 24.950 hektare.
Saat ini sekitar 26.130 hektare kawasan hutan bakau telah direhabilitasi oleh berbagai lembaga swadaya maupun pemerintah. Dan sekitar 28.900 hektare pantai berpasir sudah ditanami kembali. Namun, kegagalan penanaman yang terjadi di masa rehabilitasi dan rekonstruksi disebabkan berbagai faktor.
“Di antaranya, bibit yang tidak layak, metode penanaman yang salah, tumpang tindihnya program dan koordinasi rehabilitasi, serta tidak jelasnya kebijakan tata ruang,” kata Senior Forest Officer World Wild Fund (WWF) Indonesia Aceh Program, Dede Suhendra.
Menurut Dede, diperlukan beberapa langkah strategis dalam mengelola bakau, di antaranya, melakukan reboisasi secara terencana dan memperjelas tata ruang wilayah pesisir. Selain itu, perlu memberi akses langsung kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, serta adanya kepastian hukum atas pengelolaan hutan bakau.
“Kesulitan memperoleh bibit dalam jumlah besar, jadi kendala utama program rehabilitasi hutan bakau Aceh yang dilakukan beberapa lembaga internasional di bidang lingkungan, termasuk WIIP dan WWF”, kata Dede.[]Junaidi Mulieng
Tulisan ini ditulis tahun 2009




 Posted in:
Posted in: 

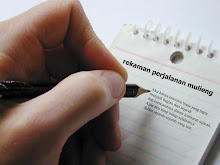
0 comments:
Post a Comment
Berikan komentar anda yang membangun....